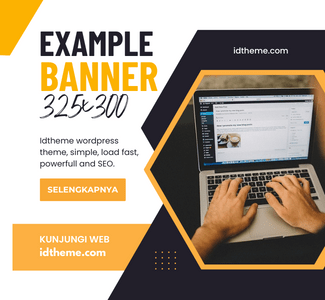Oleh: Dr. Drs. Roedy Silitonga, M.A., M.Th.
Universitas Pelita Harapan, roedy.silitonga@uph.edu
Pendahuluan
Fenomena cancel culture semakin mengemuka di Indonesia pada tahun 2025, mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menanggapi kesalahan dengan penghukuman publik tanpa memberi ruang untuk pertobatan (Kompasiana, 2025). Cancel culture, menurut Feetra Yulia dalam artikel di RRI, adalah budaya memboikot atau berhenti mendukung seseorang yang dianggap bermasalah (RRI, 2025). Ndoro Kakung menambahkan bahwa di Indonesia, cancel culture sering berfungsi sebagai ruang caci-maki, bukan sebagai ruang koreksi (Kakung, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa budaya penghukuman lebih dominan dibandingkan budaya pengampunan, yang justru dapat memperburuk polarisasi sosial dan menghalangi proses rekonsiliasi yang konstruktif. Dalam konteks ini, budaya penghukuman menghambat kesempatan untuk perubahan dan pemulihan yang sejati. Menghadapi dominasi budaya penghukuman, ajaran Yesus Kristus tentang pengampunan menawarkan solusi yang relevan. Sebagaimana tercatat dalam Lukas 7:36–50, kesadaran akan besarnya pengampunan yang diterima akan melahirkan kasih yang besar. Puncaknya terlihat pada peristiwa Jumat Agung, ketika Yesus di kayu salib berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk. 23:34). Perspektif teologi Reformed menegaskan bahwa pengampunan adalah anugerah Allah, yang diwujudkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam pengampunan, tidak hanya dalam pengajaran tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pengampunan sejati tidak mengabaikan keadilan, namun mengarahkannya pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam dunia yang lebih sering memilih penghukuman, ajaran Yesus Kristus mengundang semua pihak untuk merefleksikan bahwa pengampunan sejati bukan hanya menyelesaikan dosa pribadi, tetapi juga mendamaikan hubungan yang terpecah, memandu masyarakat menuju pemulihan, bukan penghukuman. Kuasa Pengampunan di Tengah Budaya Penghukuman
Kesalahan dan pelanggaran adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun, bagaimana seseorang merespon kesalahan tersebut menunjukkan nilai yang diyakini dan dihidupinya. Dalam Lukas 7:36–50, Yesus mengajarkan bahwa kesadaran akan besarnya pengampunan yang diterima akan melahirkan kasih yang memulihkan. Perumpamaan tentang dua orang yang berhutang mengajarkan bahwa pemahaman tentang kedalaman pengampunan menghasilkan sikap penuh pengorbanan dan belas kasihan. Puncak ajaran ini tercermin dalam peristiwa Jumat Agung, saat Yesus di salib berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk.23:34). Dalam perspektif teologi Reformed, pengampunan adalah anugerah Allah yang tidak diperoleh berdasarkan usaha manusia, tetapi sebagai perwujudan kasih dan keadilan Allah yang ditemukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Di era post-truth ini, konsep pengampunan sering kali terpinggirkan oleh dominasi cancel culture yang mengutamakan penghukuman atas kesalahan tanpa memberi ruang untuk rekonsiliasi. Masa lalu seseorang sering kali menjadi dasar untuk penghukuman sosial, tanpa memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri. Fenomena ini bertentangan dengan ajaran Kristus, yang menekankan pentingnya pertobatan dan pemulihan. Peristiwa Jumat Agung mengingatkan setiap orang bahwa meskipun dunia lebih condong pada penghukuman, Kristus justru menanggung hukuman dosa demi membuka jalan rekonsiliasi dengan Allah. Timothy Keller dalam bukunya Forgive: Why Should I and How Can I? (2022) menegaskan bahwa dalam masyarakat sekular, keadilan sering dipahami sebagai pembalasan, bukan pemulihan. Sebaliknya, kebangkitan Kristus mengaruniakan harapan baru bahwa melalui Kristus, hidup baru dan pemulihan diberikan kepada siapa yang ditentukan Allah untuk bertobat dan dipulihkan. Sementara itu, Miroslav Volf, dalam Exclusion and Embrace, menegaskan bahwa pengampunan bukan hanya soal menghapus kesalahan, tetapi membuka ruang untuk transformasi (Volf, 1996). Tanpa pengampunan, masyarakat akan terjebak dalam siklus balas dendam yang tak berkesudahan. Peristiwa Jumat Agung secara teologis menunjukkan bahwa Kristus menanggung segala dosa untuk menghentikan siklus tersebut. John Calvin dalam Institutes of the Christian Religion mengajarkan bahwa pengampunan adalah cerminan kasih karunia Allah, yang diberikan bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi sebagai tindakan kasih yang mengubah hati dan membangun kembali hubungan sosial. Dengan demikian, kebangkitan Kristus memberi jaminan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan dan umat dipanggil untuk hidup dalam pengampunan dan rekonsiliasi dengan sesama.
Pengampunan sebagai Dasar Pembaruan Sosial
Pengampunan, sebagaimana diajarkan Kristus dan ditegaskan dalam tradisi Reformed, tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi, tetapi juga membentuk kehidupan sosial, politik, dan kekristenan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pengampunan menawarkan alternatif yang menumbuhkan pertobatan, rekonsiliasi, dan pembaruan. Orang Kristen harus menjadi teladan pengampunan yang aktif, tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mewujudkan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Pengampunan sejati tidak mengabaikan keadilan, tetapi mengarahkannya kepada pemulihan, bukan pembalasan. Seperti yang ditegaskan oleh R.C. Sproul dalam The Holiness of God, pengampunan bukan hanya soal pembebasan dari hukuman, tetapi juga mengembalikan hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia, mengarah pada pemulihan yang lebih dalam dan transformatif (Sproul, 1985). Karena itu, tanpa pengampunan yang berakar pada kasih dan kebenaran Allah, upaya rekonsiliasi sosial akan tetap dangkal dan mudah terjebak dalam siklus ketidakadilan baru. Tim Chester dalam A Meal with Jesus menekankan bahwa pengampunan adalah cara Yesus menghidupkan kembali hubungan manusia, dengan mengundang orang-orang yang berdosa untuk datang kepada-Nya, mengampuni mereka, dan memulihkan mereka dalam komunitas yang penuh kasih (Chester, 2011). Bagi Chester, pengampunan bukan hanya tentang menghilangkan kesalahan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemulihan hubungan dan perubahan hati. Pandangan ini menegaskan bahwa pengampunan, yang mengarah pada rekonsiliasi, adalah elemen penting dalam kehidupan orang Kristen yang mendorong orang untuk hidup dalam komunitas yang penuh dengan kasih dan kebenaran.
Mewujudkan Budaya Pengampunan dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Pengampunan yang diajarkan Kristus harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, pengampunan menjadi dasar bagi hubungan yang sehat. Komunikasi yang terbuka, pengakuan kesalahan, dan kesempatan untuk bertumbuh setelah kegagalan menciptakan suasana yang memfasilitasi penyembuhan dan rekonsiliasi. Keluarga menjadi tempat pertama di mana nilai-nilai ini dipelajari dan diterapkan, membentuk individu yang mampu mengampuni dalam berbagai situasi. Tanpa pembiasaan pengampunan di lingkungan keluarga, individu akan cenderung membawa pola relasi yang rapuh dan penuh dendam ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Orang Kristen juga memiliki tanggung jawab besar dalam mempraktikkan pengampunan. Tidak cukup hanya mengajarkan pengampunan melalui khotbah, orang Kristen harus membangun sistem yang mendukung rekonsiliasi di antara jemaatnya. Seminar, kelas pembinaan, dan pendampingan pastoral menjadi sarana yang efektif untuk membantu jemaat menghidupi pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kerja, penerapan prinsip restorative justice lebih dari sekadar menghindari hukuman, tetapi lebih mengarah pada pemulihan hubungan yang rusak. Ini menciptakan tempat kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga membangun karakter. Sebab itu penting memiliki keseriusan membangun budaya pengampunan yang terstruktur. Hal ini diperlukan supaya orang Kristen tidak hanya melahirkan pemahaman teoritis yang tidak mengubah perilaku nyata. Di tingkat masyarakat, penting untuk mengedepankan pengampunan sebagai dasar bagi keharmonisan sosial. Melalui pendidikan publik yang menggalakkan kampanye perdamaian, forum rekonsiliasi, dan literasi emosional, pengampunan bisa menjadi alat untuk mengatasi polarisasi dan kebencian. Di tingkat pribadi, pengampunan harus dihidupi melalui doa, refleksi Alkitabiah, dan konseling Kristen. Dengan cara ini, pengampunan membawa pembaruan dalam kehidupan individu, keluarga, gereja, dan masyarakat secara keseluruhan.
Kesimpulan
Pengampunan Kristus memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada hubungan pribadi tetapi juga kehidupan sosial, politik, dan kekristenan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pengampunan menawarkan alternatif yang memperbaiki hubungan dan mendorong rekonsiliasi. Untuk mewujudkan hal ini, keluarga, lembaga kekristenan, dan masyarakat harus berkomitmen pada praktik pengampunan yang nyata, mulai dari komunikasi terbuka di keluarga hingga program rekonsiliasi di masyarakat plural dan tempat kerja yang mengutamakan pemulihan. Orang Kristen dibutuhkan sebagai teladan dengan mengajarkan pengampunan secara konkret, mendukung sesama melalui pendampingan pastoral dan pembinaan. Di tingkat masyarakat, penting untuk mengedepankan pendidikan publik tentang pengampunan, perdamaian, dan rekonsiliasi untuk mengurangi polarisasi sosial. Di tingkat pribadi, pengampunan harus dihidupi melalui doa, refleksi, dan konseling Kristen. Dengan cara ini, pengampunan yang berakar pada kematian dan kebangkitan Kristus dapat menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan penuh harapan, serta memperbaiki hubungan di berbagai aspek kehidupan.
Referensi
Chester, T. (2011). A Meal With Jesus: Discovering Grace, Community, and Mission Around the Table. Crossway.
Kakung, N. (2025, January 5). “Cancel Culture: Saat Netizen Jadi Tuhan.” Medium. https://medium.com.
Keller, T. (2022). Forgive: Why Should I and How Can I? Viking.
Sproul, R. C. (1985). The Holiness of God. Tyndale House Publishers.
Volf, M. (1996). Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation. Abingdon Press.
Tentang Penulis
Dr. Roedy Silitonga adalah teolog dan pendidik yang mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan (UPH). Ia aktif menulis dan berbicara tentang integrasi iman dan keadilan sosial dalam pendidikan Kristen, serta terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelayanan masyarakat. Fokus kajiannya mencakup teologi publik, pendidikan karakter, dan peran orang Kristen dalam masyarakat plural.